

Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi dua “kutub” problem kesehatan. Satu sisi “beban ganda” kesehatan, direpresentasikan dalam bentuk “kelebihan gizi” (baca : kelebihan berat badan dan obesitas). Tapi di sisi lainnya masih banyak dilaporkan problem stunting/tengkes yang mencerminkan defisiensi gizi. Data sementara terkait problem “dua kutub” itu, tampak dari hasil cek kesehatan gratis. Baik untuk masyarakat umum, maupun siswa.
Terbaru muncul masalah medis “dua kutub” lagi. Cacingan dan wabah campak, telah menghiasi pemberitaan berbagai media massa akhir-akhir ini. Dua penyakit “kuno” tersebut, belum mampu dieliminasi oleh negara. Sementara pemerintah kini sangat fokus menangani penyakit “modern”, dengan membangun berbagai fasilitas kesehatan canggih. Sebab penyakit kardiovaskuler, antara lain jantung dan stroke, kini menjadi “pembunuh” terbanyak rakyat Indonesia.
Tengkes, cacingan, dan campak, memerlukan tata laksana utama promotif dan preventif. Sementara problem kardiovaskuler memerlukan dana besar untuk pos kuratif dan rehabilitatif. Semuanya akan “baik-baik” saja, jika terjadi keseimbangan yang optimal.
Cacingan
Problem cacingan berat terjadi pada seorang balita empat tahun di Sukabumi. Konon lebih dari satu kilogram cacing gelang (Ascaris lumbricoides), ditemukan pada anak malang itu. Sayangnya, Raya nama balita itu, tidak tertolong.
Sejatinya investasi cacing gelang di Indonesia, cukup sering didapatkan. Data tahun 2017 menyatakan, prevalensinya cukup tinggi. Sekitar 60-90 persen. Sementara ini belum ada data terbaru. Mestinya pencegahannya relatif mudah. Asalkan masyarakat diberikan pemahaman tentang siklus hidup parasit nematoda tersebut. Keluarnya telur cacing bersama tinja seseorang yang terpapar, merupakan tahap awal penularan pada individu lainnya. Jika tinja itu mencemari tanah, maka telur cacing menjadi bentuk infektif. Secara tidak sengaja, seseorang berpotensi tertular, bila tertelan telur yang infektif. Di dalam saluran cerna, telur akan menetas menjadi larva. Selanjutnya larva akan menembus usus dan “bermigrasi” menuju aliran darah. Alveolus (gelembung paru), menjadi tempat transitnya. Kondisi itulah yang memicu batuk pada Raya. Batuk yang mengandung larva, cukup penting untuk membuat diagnosis. Cacing dewasa akan tumbuh berkembang, jika larva “bermigrasi” lagi ke usus. Parasit tersebut akan “kawin” (kopulasi) dan menghasilkan telur. Demikian, siklus hidup parasit yang akan berulang terus. Gejala yang ditimbulkan tergantung letak parasit di tubuh manusia. Jika dalam jumlah besar, dapat menyumbat saluran cerna. Tidak jarang harus memerlukan operasi.
Jadi kata kunci program promotif dan preventif yang berbiaya relatif murah, dapat dilakukan pada publik. Edukasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang berkesinambungan, perlu diterapkan.
Wabah campak
Kini negara kita diterpa wabah campak. Bukan hanya di Kabupaten Sumenep saja. Jakarta, Tangerang, dan 42 wilayah lainnya, dilaporkan terjadi hal serupa. “Hanya” ada dua pemikiran dasar, mengapa campak merebak lagi.
Pertama. Angka penularan global yang meningkat. Sebelum terjadi di Indonesia, kasus wabah terjadi di Amerika Serikat dan Meksiko. Kejadiannya sekitar bulan Maret 2025. Wabah di AS tersebut bukanlah untuk pertama kalinya. Faktanya pernah terjadi wabah serupa tahun 2011, 2014, 2018, 2019, dan terakhir setahun yang lalu. Padahal campak telah dinyatakan hilang/eradikasi di AS pada tahun 2000.
Eropa juga mengalami nasib yang sama. Berdasarkan rilis Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), hampir 60 ribu kasus terdeteksi di 45 dari 53 negara Kawasan Benua Biru. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), beberapa tahun terakhir ini telah terjadi lonjakan kasus campak di seluruh dunia. Pada tahun 2023, telah menginfeksi sebanyak 10,3 juta orang.
Kedua. Kerentanan penduduk dunia terpapar campak, akibat menurunnya cakupan vaksinasi. Fakta epidemiologi membuktikan, semakin banyak individu yang tidak divaksinasi, semakin meningkat pula risiko terjadinya wabah. Ada model riset yang mampu memprediksi interaksi kedua fenomena itu. Contohnya bila cakupan vaksinasi MMR mencapai 97 persen, peluang terjadinya wabah hanya sebesar 16 persen. Namun sebaliknya bila cakupannya cuma 70 persen, peluang terjadinya wabah bisa meningkat hingga 78 persen. Sebanyak 95 persen kasus campak yang dilaporkan di AS, ternyata belum pernah dilakukan vaksinasi. Sama dengan yang terjadi di Sumenep. Mayoritas yang terpapar adalah yang belum dilakukan vaksinasi. Lebih-lebih pada individu yang mengalami komplikasi hingga kematian.
Di antara penyakit menular, campak disebabkan virus yang memiliki daya tular tertinggi. Bahkan kecepatan merebaknya, melampaui virus penyebab COVID-19. Bila seseorang telah terjangkit, bisa diprediksi sebanyak 90 persen orang di sekitarnya akan terpapar pula. Khususnya pada individu yang tidak memiliki daya imunitas terhadap campak. Risiko penularan virus, terutama terjadi sejak empat hari sebelum hingga empat hari setelah munculnya ruam-ruam. Model penularannya pun persis sama dengan COVID-19. Bisa melalui percikan saat batuk, bersin, atau saat berbicara. Transmisi virus juga bisa terjadi melalui permukaan benda-benda yang terkena percikan, lalu menyentuh mata, hidung, atau mulut individu sekitarnya.
Pada individu dengan imunitas yang tidak sempurna (immunocompromised), risiko komplikasi campak bisa meningkat tajam. Misalnya terjadi diare berat, pneumonia (radang paru), radang otak, infeksi selaput lendir mata, hingga mengalami kebutaan.
Hingga kini vaksinasi MMR (Mumps/gondongan, Measles, dan Rubela), merupakan modalitas preventif terbaik.
Semoga dengan dilakukannya outbreak response immunization (ORI), negara kita segera terbebas dari wabah.
—–o—–
*Penulis:
- Staf pengajar senior di Divisi Alergi-Imunologi Klinik, Departemen/KSM Ilmu Penyakit Dalam FK Unair/RSUD Dr. Soetomo – Surabaya
- Magister Ilmu Kesehatan Olahraga (IKESOR) Unair
- Penulis buku:
– Serial Kajian COVID-19 (tiga seri)
– Serba-serbi Obrolan Medis
– Catatan Harian Seorang Dokter

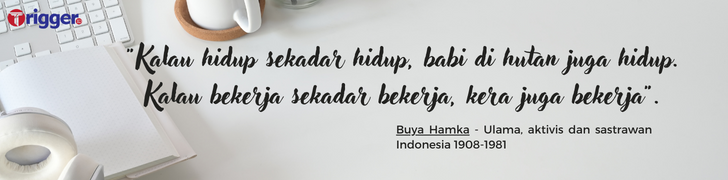

Tinggalkan Balasan