

Debat Capres sesi terakhir tanggal 4 Februari 2024 lalu, masih menyisakan banyak pertanyaan. Dalam bidang kesehatan, tampak masih adanya dikotomi ranah pelayanan, antara preventif dan kuratif. Semua Capres sependapat, bahwa aspek preventif dan promotif lebih diutamakan daripada kuratif.
Di sisi lain, ada janji pembangunan rumah sakit (rumkit) modern di setiap kabupaten/kota. Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) modern pun, akan dibangun di setiap desa di seluruh Indonesia. Visi itu disampaikan dalam situasi dihapusnyamandatory spending bidang kesehatan dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Kendala lain yang patut diperhitungkan adalah menyangkut kuantitas, kompetensi,dan distribusi tenaga medis yang belum merata di semua daerah. Apakah mungkin janji tersebut bisa terealisasi ?
Sejak awal didirikannya, Puskesmas mempunyai misi menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif. Sebaliknya, rumkit difokuskan pada pelayanan penyembuhan penyakit, sekaligus pemulihannya (kuratif-rehabilitatif) hingga mencapai kondisi sebelum sakit. Meski demikian,tidak semua target ideal itu akan dapat tercapai. Tergantung pada tipe dan derajat penyakitnya, masih terbuka risiko terjadinya gejala sisa/”kecacatan”. Seyogianya ada keseimbangan dan relasi yang dinamis,serta sekala prioritas antara pelayanan preventif dan kuratif.
Masyarakat berasumsi, semakin modern suatu rumah sakit, akan menghasilkan pelayanan kuratif yang lebih maksimal. Tidak hanya harus memiliki sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni, tipe rumkit semacam itu juga mesti didukung peralatan yang serba canggih/memadai. Konsekuensinya mesti ditopang modal yang sangat besar, sehingga membuka peluang pendanaannya oleh investor yang sarat dengan kepentingan ekonomi belaka.Walaupun mungkin pelayanan medisnya dapat disokong oleh suatu asuransi kesehatan, bisa diprediksi pola tersebut tidak akan bisa dinikmati oleh semua masyarakat secara merata.Hanya masyarakat dengan kelas ekonomi menengah ke atas yang mungkin bisa memanfaatkannya.
Semua profesional medis sudah sangat memahami, bahwa paradigma pencegahan suatu penyakit akan jauh lebih efektif dan efisien dari sisi biaya, bila dibandingkan aspek kuratif. Bagi penyelenggara layanan kesehatan di negara mana pun di seluruh dunia, masih meyakini kaidah itu.Modalitas tersebut sangat sesuai untuk diterapkan, terutama di negara-negara dengan pendapatan ekonomi menengah ke bawah. Pandemi COVID-19 merupakan contoh yang paling riil. Pendekatan preventif dengan melakukan vaksinasi masal, akan jauh lebih ekonomis bila dibandingkan dengan pengobatan kuratif. Bahkan “hanya” dengan melakukan protokol kesehatan yang baik dan benar, sudah mampu mencegah paparan COVID-19. Sebaliknya biaya pengobatan COVID-19 yang memakan dana besar, berkaitan dengan perawatan di ICU dan penggunaan ventilator. Belum lagi terhadap obat-obatan dan dukungan peralatan medis lainnya.
Sebagai salah satu contoh, saat inipenyakit kardiovaskuler (PKV) menempati peringkat pertama dalam hal pembiayaan, sekaligus penyebab kematiannya di Indonesia. Kalau negara berencana mendirikan banyak rumkit modern, pembiayaannya tidak akan sepadan dengan hasil yang akan diperoleh. Pasalnya PKV (jantung, pembuluh darah, stroke) yang terjadi, merupakan kulminasi dari suatu perjalanan waktu yang panjang dari berbagai macam faktor risiko. Faktor-faktor risiko itu bisa dikategorikan dalam bentuk yang tidak dapat dimodifikasi (genetik/ras, usia, jenis kelamin) dan yang dapat dimodifikasi (aktivitas fisik, merokok, konsumsi alkohol, pola makan, stres). Dari aspek hulu, semua faktor risiko tersebut saling berinteraksi, sehingga pada posisi hilirnya dapat memicu timbulnya “penyakit antara” (hipertensi, diabetes, berat badan berlebih, kelainan kadar lemak darah).PKV merupakan kulminasi dari berbagai macam “penyakit antara” tadi.Sejatinya keberhasilan mengendalikan berbagai macam faktor risiko, merupakan wujud investasi jangka panjang terhadap pencegahan terjadinya PKV.
Pemberdayaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
Penerapan suatu kebijakan menekan dampak PKV, seyogianya didasarkan pada aspek kronologi dan didukung data yang valid. Sayangnya negara kita tidak memiliki data dasar epidemiologi yang memadai, sebagai unsur deteksi dini. Data tersebut menyangkut profil berbagai faktor risiko yang sebenarnya bisa ditelisik jauh ke belakang. Itu bisa diupayakan sejak awal dari bangku sekolah. UKS bisa ditingkatkan pendayagunaannya, agar mampu mendeteksi secara dini berbagai faktor risiko PKV pada para siswa (SD, SMP, SMA). Cara pelaksanaannya pun cukup mudah untuk diterapkan, praktis, dan efisien dari sisi pendanaan. Sebagai salah satu contoh adalah menilai indeks masa tubuh (IMT), melalui pengukuran tinggi dan berat badan secara berkala.Rumus IMT adalah berat badan (dalam kilogram) dibagi tinggi badan (dalam meter kuadrat). Disebut normal bila memiliki IMT antara 18,5-25,0. Di atas angka 25,0 dikatakan memiliki berat badan berlebih. Sebaliknya bila kurang dari 18,5 disebut kurus. Selanjutnya data tersebut dianalisis dan mestinya dilakukan secara berkesinambungan, mulai tingkat SD hingga SMA. Bahkan mungkin sampai perguruan tinggi atau dalam bentuk data pribadi yang melekat sepanjang hidupnya. Dengan bantuan teknologi informasi yang semakin canggih, data tersebut bisa digunakan untuk mengintervensi secara dini PKV. Untuk itu diperlukan kesesuaian visi dan kerja sama lintas sektoral,dalam mewujudkan kebijakan tersebut.
Dalam berbagai riset epidemiologi, ada relasi yang kuat antara IMT dengan kejadian PKV. Seseorang dengan IMT yang melebihi angka normal, berisiko mengalami penyakit kardiovaskuler bila dibanding yang memiliki IMT normal. Dalam praktik di lapangan, pengendalian berat badan dapat diupayakan sejak dini melalui modifikasi gaya hidup (lifestyle). IMT sangat dipengaruhi oleh kebiasaan berolah raga dan pola makan sehari-hari. Menurut Global Status Reporton Physical Activity 2022 yang dirilis Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sekitar 81 persen remaja melakukan aktivitas fisik di bawah standar. Di sisi lain, mayoritas mereka menggemari makanan siap saji yang memiliki kandungan kalori, lemak dan garam yang tinggi, tetapi miskin nilai nutrisi. Dalam jangka panjang, kedua faktor tersebut berisiko tinggi memicu terjadinya “penyakit antara” yang berujung pada terjadinya PKV.
Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan bagian tugas utama UKS. Peran tersebut akan lebih paripurna, bila dilengkapi dengan data IMT siswanya secara berkala.Adanya deviasi IMT, merupakan suatu indikasi dini untuk melakukan intervensi yang memerlukan kerja sama dengan Puskesmas. Demikian seterusnya dapat dilakukan penatalaksanaan secara berjenjang di fasilitas kesehatan yang lebih tinggi,bila memang ada indikasi medis.
Berbagai strategi pengelolaan suatu penyakit, bisa dilakukan dari semua lini (preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif). Di tengah-tengah keterbatasan pembiayaan dan berbagai kendala SDM penopangnya, perlu kebijakan yang berdasarkan pada sekala prioritas. Kerja sama lintas sektoral dan keterlibatan masyarakat perlu digairahkan, agar visi mencapai kesehatan masyarakat Indonesia yang lebih baik dapat tercapai.
—–o—–
*Penulis :
Staf pengajar senior di:
Divisi Alergi-Imunologi Klinik, Departemen/KSM Ilmu Penyakit Dalam FK Unair/RSUD Dr. Soetomo – Surabaya
Anggota Advisory Board Dengue Vaccine
Penulis buku:
* Serial Kajian COVID-19 (sebanyak tiga seri)
* Serba-serbi Obrolan Medis
Serba-serbi Obrolan Medis

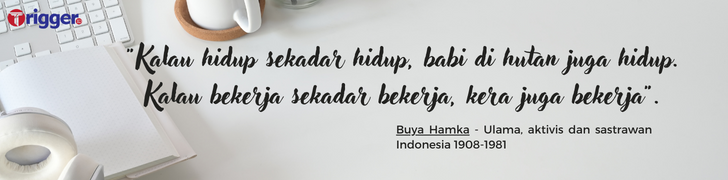

Tinggalkan Balasan