

Ibarat anggaran belanja kebutuhan rumah tangga, lazimnya bisa diprediksi dan idealnya mesti telah dipersiapkan. Untuk keperluan yang sifatnya “wajib”, harusnya mendapatkan prioritas utama dibanding kebutuhan sekunder. Dana wajib tersebut dapat tercukupi, bila anggota keluarga (khususnya yang memperoleh penghasilan) dapat bekerja dalam kondisi sehat. Sayangnya kondisi “ideal” tersebut, tidak bisa dinikmati oleh semua orang/keluarga di Indonesia. Misalnya untuk kebutuhan susu.Bila tidak dianggarkan, berpotensi menimbulkan masalah kesehatan anak. Mungkin pula biaya untuk membeli obat anti nyamuk, agar terhindar dari penularan demam berdarah dengue (DBD), tidak dapat terpenuhi juga.
Mandatory spending kesehatan (MSK), merupakan kewajiban pemerintah mengalokasikan minimal sebesar lima persen dana APBN. Anggaran itu diperlukan guna menunjang status kesehatan rakyat Indonesia.Bentuknya dapat berupa pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya bagi penduduk miskin, warga usia lanjut, atau anak-anak terlantar.Penurunan angka stunting, kematian ibu saat melahirkan, serta kematian bayi, merupakan target alokasi anggaran wajib tersebut. Anggaran itu juga diperlukan bagi penanggulangan bencana, kejadian luar biasa (KLB) dan wabah. Riset, pengembangan, dan inovasi bidang kesehatan, memerlukan pendanaan yang alokasinya juga dari anggaran wajib tersebut.Dalam level daerah, anggaran wajib dipatok sebesar minimal sepuluh persen dari APBD. Semua alokasi anggaran tersebut (baik APBN atau APBD), diperhitungkan di luar gaji aparatur negara bidang kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023, MSK kini ditiadakan. Pemerintah beralasan, kebijakan itu diambilantara lain karena sempitnya ruang fiskal dan demi efisiensi anggaran kesehatan. Adanya jaminan kesehatan nasional (JKN), memperkuat diberlakukannya UU tersebut.
Kini negara kita dihadapkan pada masalah melonjaknya insiden DBD. Terhitung hingga minggu ke-17 tahun 2024 jumlahnya sebanyak 88.593 kasus, dengan 621 kematian. Seminggu sebelumnya tercatat 76.132 kasus, dengan angka kematian sebesar 540 jiwa. Kemudian berturut-turut tercatat 53.131 kasus (26 Maret 2024), dan 62 ribu kasus yang disertai 475 kematian (15 April 2024). Sangat mungkin kasus yang terdeteksi, sebenarnya hanya merupakan puncak fenomena gunung es. Pasalnya sebagian besar paparan virus dengue, justru berlangsung tanpa gejala atau hanya berupa demam ringan saja. Umumnya masyarakat hanya menganggapnya sebagai “penyakit biasa” yang tidak terpikirkan akibat paparan dengue. Patut menjadi perhatian, meski gejalanya ringan, berpotensi sebagai sumber penularan virus dengue.
Sebagai perbandingan, insiden DBD pada pekan ke-17 tahun 2023 yang lalu, tercatat hanya 28.579 kasus. Angka kematiannya sebanyak 209 jiwa.
Kasus-kasus yang kini tercatat sebagai DBD di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), hampir keseluruhannya merupakan kasus rawat inap di rumah sakit. Hanya sebagian kecil saja yang pelaporannya berasal dari Puskesmas atau fasilitas kesehatan (faskes) lainnya. Prosedurnya, rumah sakit atau Puskesmas melaporkan angka kejadian DBD secara berkala ke Dinas Kesehatan setempat.Selanjutnya secara berjenjang melaporkannya kepada Kemenkes. Sayangnya sistem pencatatan dan pelaporan (surveilans) semacam itu, masih menjadi kendala bagi sebagian besar Puskesmas di Indonesia. Banyak faktor yang memengaruhi. Misalnya petugas surveilans harus berfungsi ganda merangkap tugas rutin pelayanan kesehatan lainnya, sehingga kurang fokus.Kemampuan mengolah, menyajikan, dan menganalisis data, sering kali juga tidak dapat dilakukan secara optimal.
Surveilans merupakan strategi penting memantau perkembangan epidemiologi DBD dari waktu ke waktu. Itu diperlukan pemangku kebijakan dalam perencanaan, pencegahan, dan pemberantasan DBD. Bila sistem tersebut tidak mampu menyediakan data/informasi terkini dan akurat, maka kebijakan yang akan diputuskan berpotensi mengalami kendala.
Puskesmas atau faskes lainnya, tidak semuanya dilengkapi sarana penunjang laboratorium (tes cepat) untuk mendiagnosis DBD. Kasus yang diduga DBD atau terkonfirmasi positif melalui tes cepat, akan dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan selanjutnya. Meski dapat melakukan diagnosis, klinik-klinik pengobatan ataupun praktik dokter perorangan,tidak memiliki akses pelaporan secara langsung ke instansi terkait.
Pemberlakuan sistem surveilans DBD, sangat berbeda dengan Covid-19 saat pandemi. Saat itu seluruh faskes yang melakukan pemeriksaan tes cepat antigen atau PCR, wajib segera melaporkan hasilnya pada sistem NAR (New-All Record). Datanya langsung dimasukkan dan terafiliasi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Data yang diperolehsaat itu, dapat segera diikuti perkembangannya dalam waktu yang relatif singkat. Keputusan yang akan diambil pemangku kebijakanpun, dapat disesuaikan dengan cepat berdasarkan data terkini dari seluruh penjuru tanah air. Bisa diasumsikan, angka kejadian DBD yang saat ini dipublikasikan Kemenkes, berasal dari kompilasi data kasus DBD beberapa waktu sebelumnya. Jadi sifatnya bukan data/informasi terkini. Datanya pun belum tentu akurat.
KLB
Kejadian Luar Biasa (KLB), merupakan penerapan status peristiwa penyakit yang merebak dan berpotensi berkembang menjadi wabah yang kondisinya semakin meluas dan lebih parah. KLB bisa diartikan sebagai peringatan/tahapan menuju wabah. Aturannya berlandaskan pada Permenkes RI No.949/MENKES/SK/VII/2004. Salah satu poin penetapannya, bila memenuhi kriteria peningkatan kejadian penyakit/kematian, sebanyak dua kali lipat/lebih dibandingkan periode waktu sebelumnya. Mestinya situasi DBD saat ini, sudah layak ditetapkan sebagai KLB. Dasarnya terjadi peningkatan kasus DBD yang sudah mencapai tiga kali lipat, bila dibandingkan dengan periode waktu yang sama setahun sebelumnya. Beberapa daerah di Indonesia saat ini, telah ditetapkan statusnya sebagai KLB DBD.
Penetapan status KLB, memiliki suatu konsekuensi. Anggaran pembiayaan semua kasus yang terpapar DBD, mestinya dibebankan dalam MSK yang kini sudah dihapus. Pembiayaannya bukan lagi ranah JKN. Sebaliknya bila statusnya tidak ditetapkan sebagai KLB, pemerintah daerah tidak bisa mengajukan anggaran belanja tidak terduga. Anggaran itu penting untuk program mitigasi DBD sekala besar dan masif. Dengan dihapusnya MSK, tidak ada lagi alokasi anggaran untuk mitigasi KLB. Alternatifnya, pemerintah harus menggunakan sumber dana dari anggaran lainnya, demi mencegah terjadinya wabah DBD.
Selain pemberantasan sarang nyamuk, mestinya vaksinasi DBD menjadi pilar utama pencegahan penyakit. Dengan dihapusnya MSK, integrasi vaksinasi DBD dalam program imunisasi nasional (PIN) berpotensi terhambat.
—–o—–
*Penulis :
Staf pengajar senior di:
Divisi Alergi-Imunologi Klinik, Departemen/KSM Ilmu Penyakit Dalam FK Unair/RSUD Dr. Soetomo – Surabaya
Anggota Advisory Board Dengue Vaccine
Penulis buku:
* Serial Kajian COVID-19 (sebanyak tiga seri)
* Serba-serbi Obrolan Medis

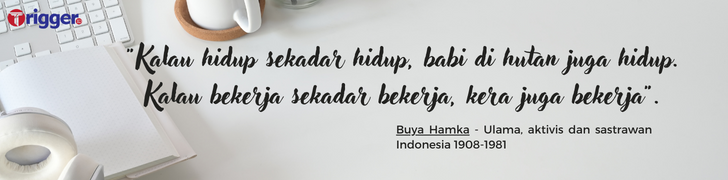

Tinggalkan Balasan