

“Dok, penyakit alergi biasa itu seperti apa ya” ? Secara refleks pikiran saya langsung tertuju pada penyakit yang saat ini dialami Jokowi, Presiden RI ke-7. Karena tidak segera menjawab, pertanyaan berikutnya segera menyusul. “Dok, apa sih Sindrom Stevens-Johnson” (SSJ) itu ? Apa pula dengan vitiligo atau penyakit autoimun ? Saya masih juga tercekat. Meski sebagai konsultan Alergi-Imunologi, tidak mudah bagi saya untuk menjawabnya. Jika terkait aspek teori ilmiahnya, itu sudah menjadi bagian dari kewajiban profesi saya sehari-hari. Tetapi menyangkut mantan orang nomor satu di Indonesia, tentu bukan kapasitas saya untuk menjelaskannya. Mestinya itu merupakan wewenang dokter yang merawatnya. Dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP), begitulah sebutannya. Bisa pula didelegasikan pada seorang juru bicara yang telah diizinkan dan dipercaya keluarga Jokowi, untuk menjelaskannya ke publik. Lalu, bagaimanakah peran dokter Kepresidenan ? Meski tidak lagi menjabat, beliau dan keluarga intinya masih berhak atas fasilitas negara berupa pelayanan medis. Aturannya berdasarkan Perpres No.18 Tahun 2018, tentang Dokter Kepresidenan.
Hak privasi
Bisa jadi pertanyaan seseorang yang mengaku sebagai jurnalis tadi, mewakili sebagian besar masyarakat Indonesia. Tidak salah jika publik ingin tahu. Di era keterbukaan, beragam informasi amat berharga bagi masyarakat. Meski demikian, ada batasan tertentu atau perkecualian. Informasi yang bersifat pribadi (misalnya data pribadi, termasuk kesehatan), adalah salah satu di antaranya. Dasarnya adalah Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
Data kesehatan seseorang, tergolong dalam hak privasi. Sebab bersifat pribadi dan “sangat sensitif”. Implementasinya harus memerlukan perlindungan khusus. Hak privasi kesehatan mencakup pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapannya. Demikian pula menyangkut dokter yang merawatnya. Sosok yang dikenal dengan jas putih itu, berkewajiban menjaga kerahasiaan informasi medis pasien. Perkecualian tetap ada, terhadap hal-hal yang khusus. Data medis dapat dibuka untuk kepentingan pasien sendiri. Misalnya terkait pembiayaan asuransi. Bisa juga karena “pro justitia”, guna kepentingan penegakan hukumnya. Perlindungan hukumnya didasarkan atas Undang-Undang No.27 Tahun 2022. Isinya mengatur perlindungan data kesehatan dan memberikan sanksi bagi pelanggaran privasi datanya.
Paradigma hak privasi yang terjadi pada Jokowi, mungkin berbeda dengan saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sakit. Pada tahun 2021 silam, Presiden ke-6 tersebut menyatakan mengidap kanker prostat. Informasinya dilakukan secara terbuka oleh staf pribadinya ataupun oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Dokter Kepresidenan pun, terlibat langsung sejak awal hingga proses penyembuhan. Meski akhirnya menjalani operasi di Mayo Clinic- Amerika Serikat, semua biaya ditanggung negara sesuai peraturan yang berlaku. Pun demikian dengan mantan ibu negara, Ani Yudhoyono. Beliau wafat, akibat kanker darah yang diidapnya sejak beberapa waktu lamanya. Meski harus dirawat hingga berpulang tanggal 1-6-2019 di National University Hospital-Singapura, semua hak pembiayaannya tetap ditanggung negara. Liputannya bersifat terbuka, sehingga seluruh publik tanah air dapat mengikuti tahap demi tahap perkembangannya. Dokter Kepresidenan pun, terlibat dalam perawatan sejak awal hingga akhir hayat beliau.
Lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya. Berbeda dengan di Indonesia, data medis Pemimpin Amerika Serikat jika dibuka berpotensi menjadi komoditas politik. Informasi kesehatan para Presiden Negara Paman Sam, kerap kali justru dirahasiakan. Kebohongan publik sudah menjadi bagian dari intrik politik sang pemimpin atau staf/orang dekatnya. Termasuk juga dokter-dokter yang merawatnya. Contohnya saat Donald Trump terpapar Covid-19 pada awal Oktober 2020. Presiden kontroversial itu awalnya menganggap remeh virus corona. Ketika pengenaan masker diwajibkan, sang Presiden justru tidak memedulikannya. Bahkan sering meledek Joe Biden, lawan politiknya yang disiplin memakai masker. Akhirnya saat harus dirawat intensif akibat penyakit pandemi itu, kebohongan publik tidak dapat ditutup-tutupinya lagi.
SSJ
Mayoritas SSJ timbul akibat reaksi adversi terhadap obat. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), reaksi adversi obat (adverse drug reaction/ADR), terjadi tanpa suatu kesengajaan. Bisa menimpa pada siapa pun juga, tanpa terkecuali. Tidak pula dapat diprediksi. Manifestasi klinisnya bisa sangat berbahaya. Bahkan berisiko fatal dan mengancam jiwa. Kulit yang melepuh seperti mengalami luka bakar, adalah gambaran klinis yang khas.
Berbagai unsur dalam obat, akan mengalami biotransformasi menghasilkan efek terapi. Struktur kimiawinya juga berubah, menjadi bentuk metabolit yang lebih mudah dieliminasi. Prosesnya melibatkan berbagai enzim (terutama di lever). Pada kasus yang amat jarang terjadi, beberapa metabolit obat berikatan dengan sel-sel kulit. Persenyawaannya berubah menjadi antigen/alergen. Tak pelak, sistem imun akan meresponsnya sebagai “lawan” yang harus disingkirkannya. Singkatnya, pola mekanismenya sangat mirip dengan penyakit alergi atau autoimun. Seperti juga luka bakar, semakin luas permukaan tubuh yang terlibat, semakin buruk pula prognosisnya.
Saat stadium penyembuhan, lesi SSJ bisa meninggalkan bekas perubahan warna kulit. Bisa berwarna putih, mirip vitiligo. Bisa pula merah muda, coklat, kemerahan, atau keunguan. Hal itu sebagai akibat kulit tidak memiliki pigmen melanin seperti semula.
—–o—–
*Penulis:
- Staf pengajar senior di Divisi Alergi-Imunologi Klinik, Departemen/KSM Ilmu Penyakit Dalam FK Unair/RSUD Dr. Soetomo – Surabaya
- Magister Ilmu Kesehatan Olahraga (IKESOR) Unair
- Penulis buku:
– Serial Kajian COVID-19 (tiga seri)
– Serba-serbi Obrolan Medis
– Catatan Harian Seorang Dokter

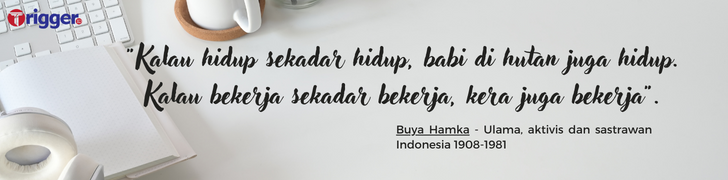

Tinggalkan Balasan