

Kini Indonesia kembali menghadapi kejadian luar biasa (KLB) campak. Sebanyak 46 wilayah telah menjadi sasarannya. Kali ini pulau Madura, khususnya Sumenep hingga Pamekasan, menjadi “episentrumnya”. KLB sebelumnya tercatat tahun 2022. Tetapi saat itu “hanya” menimpa di 31 provinsi saja dan terkonfirmasi 4800 kasus. Setahun kemudian, di tahun 2023, trennya cenderung meningkat. Sebanyak 10.600 kasus telah terdeteksi. Setelah menurun sejenak di tahun 2024 (“hanya” tercatat sebanyak 3500 kasus), kini terjadi lonjakan sejak Agustus 2025.
Mengapa KLB campak selalu berulang? Begitu sulitkah memitigasi penyakit “kuno” tersebut? Padahal hingga kini vaksinasi terbukti merupakan modalitas terpilih yang paling efektif dan efisien dari sisi biaya, dalam memberantas penyakit menular. Contoh paling dramatis adalah eradikasi cacar. Penyakit itu sudah ada sejak tiga ribu tahun yang lalu. Hanya saja upaya pemberantasan baru terlaksana pada pertengahan abad ke-20. Sebagai tulang punggung mitigasi, vaksin cacar telah mampu mengakhiri pandemi penyakit ganas itu. Korban meninggal sekitar 500 juta penduduk dunia. Dibutuhkan waktu selama 200 tahun, untuk mengenyahkannya. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendeklarasikannya pada 8 Mei 1980.
Peran vaksinasi juga terbukti dominan, dalam memitigasi pandemi COVID-19. Meski tingkat efektivitasnya tidak mencapai seratus persen, namun vaksinasi telah mampu mengakhiri pandemi. Misinformasi dan munculnya kelompok anti vaksin, mewarnai kendala penerapan vaksinasi COVID-19. Polanya mungkin berbeda di setiap negara. Kini kendala yang serupa mesti dihadapi ketika memberantas wabah campak. Tidak hanya oleh Indonesia. Tetapi juga di beberapa negara lainnya.
Wabah campak
“Hanya” ada dua pemikiran dasar, mengapa campak selalu merebak lagi.
– Pertama. Angka penularan global yang meningkat. Sebelum terjadi di Indonesia, wabah terjadi di Amerika Serikat dan Meksiko. Kejadiannya sekitar bulan Maret 2025. Wabah tersebut bukanlah untuk pertama kalinya. Faktanya pernah terjadi wabah serupa tahun 2011, 2014, 2018, 2019, dan terakhir setahun yang lalu. Padahal campak telah dinyatakan eradikasi di AS pada tahun 2000.
Eropa juga mengalami nasib yang sama. Berdasarkan rilis WHO, hampir 60 ribu kasus terdeteksi di 45 dari 53 negara Kawasan Benua Biru. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), beberapa tahun terakhir ini telah terjadi lonjakan kasus campak di seluruh dunia. Pada tahun 2023, telah menginfeksi sebanyak 10,3 juta orang.
–Kedua. Kerentanan penduduk dunia terpapar campak, akibat menurunnya cakupan vaksinasi. Fakta epidemiologi membuktikan, semakin banyak individu yang tidak divaksinasi, semakin meningkat pula risiko terjadinya wabah. Ada model riset yang mampu memprediksi interaksi fenomena keduanya. Contohnya bila cakupan vaksinasi MMR mencapai 97 persen, peluang terjadinya wabah hanya sebesar 16 persen. Namun sebaliknya bila cakupannya cuma 70 persen, peluang terjadinya wabah bisa meningkat hingga 78 persen. Sebanyak 95 persen kasus campak yang dilaporkan di AS, ternyata belum pernah dilakukan vaksinasi. Sama halnya dengan yang terjadi di Sumenep dan Pamekasan, atau daerah-daerah lainnya. Mayoritas yang terpapar adalah yang belum dilakukan vaksinasi. Lebih-lebih pada individu yang mengalami komplikasi hingga kematian.
Di antara penyakit menular, campak disebabkan virus yang memiliki daya tular tertinggi. Bahkan kecepatan merebaknya, melampaui COVID-19. Bila seseorang telah terjangkit, bisa diprediksi sebanyak 90 persen orang di sekitarnya akan tertular. Khususnya pada individu yang tidak memiliki daya imunitas terhadap campak. Risiko penularan virus, terutama terjadi sejak empat hari sebelum, hingga empat hari setelah munculnya ruam-ruam. Model penularannya pun persis sama dengan COVID-19. Bisa melalui percikan saat batuk, bersin, atau saat berbicara. Transmisi virus juga bisa terjadi melalui permukaan benda-benda yang terkena percikan, lalu menyentuh mata, hidung, atau mulut individu sekitarnya.
Pada individu dengan imunitas yang tidak sempurna (immunocompromised), risiko komplikasi campak bisa meningkat tajam. Misalnya terjadi diare berat, pneumonia (radang paru), radang otak, infeksi selaput lendir mata, kebutaan, hingga kematian.
Misinformasi vaksin
Selama dua dekade terakhir, Robert F. Kennedy Jr (RFK) mempromosikan teori pemicu autisme. Sosok yang kini menjabat Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (Menkes) negara Paman Sam itu, gencar menuding thimerosal/tiomersal sebagai penyebabnya. Thimerosal merupakan substansi yang digunakan sebagai pengawet vaksin. Gagasan itu banyak dilontarkan RFK dan kelompok anti vaksinnya, melalui aktivitasnya di Children Health Defense. Meski melalui riset yang kredibel, telah dapat dibuktikan tidak ada kaitannya antara autisme dengan thimerosal. Tidak tanggung-tanggung, WHO, CDC AS, dan sejumlah peneliti dunia, tidak menemukan hubungannya melalui riset kedokteran berbasis bukti (evidence-based medicine/EBM). Tetapi kenyataan di lapangan berbicara lain. Para orang tua di AS jadi enggan memvaksinasi anak-anak mereka, karena khawatir akan efek samping thimerosal yang berbasis merkuri. Agar tidak berdampak lebih luas terhadap layanan vaksinasi, kini thimerosal mulai digantikan peranannya secara bertahap, menggunakan pengawet vaksin lainnya.
Indonesia berbeda dengan AS. Misinformasi vaksin, justru dikaitkan dengan isu tidak halal, takut efek samping, dan merasa tidak membutuhkan. Padahal sudah dijamin oleh pihak yang berwenang, bahwa pendapat sebagian masyarakat itu tidak benar.
Hingga kini vaksinasi MMR (Mumps/gondongan, Measles/campak, dan Rubella/campak Jerman), merupakan modalitas preventif terbaik.
Semoga dengan dilakukannya outbreak response immunization (ORI), negara kita segera terbebas dari wabah.
—–o—–
*Penulis:
- Staf pengajar senior di Divisi Alergi-Imunologi Klinik, Departemen/KSM Ilmu Penyakit Dalam FK Unair/RSUD Dr. Soetomo – Surabaya
- Magister Ilmu Kesehatan Olahraga (IKESOR) Unair
- Penulis buku:
– Serial Kajian COVID-19 (tiga seri)
– Serba-serbi Obrolan Medis
– Catatan Harian Seorang Dokter

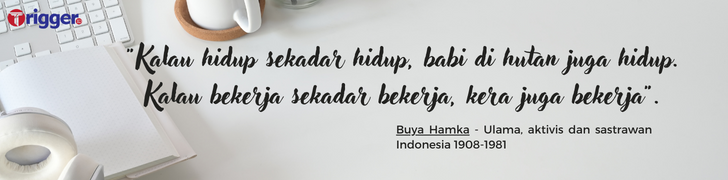

Tinggalkan Balasan