

Tidak jarang terjadi, seseorang yang sedang terlibat masalah hukum mengalami nyeri dada. Keluhan tersebut bisa timbul, saat sedang menjalani proses hukum yang terdiri dari beberapa tahap. Mulai dari fase penyelidikan, hingga yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Pada hakikatnya, seseorang tersebut berhak penuh mendapatkan layanan kesehatan. Tidak dibenarkan adanya diskriminasi. Harus diperlakukan sama, seperti masyarakat lainnya. Sebab, selain merupakan perlindungan terhadap hak asasi manusia, negara pun memiliki tanggung jawab. Landasan hukumnya adalah UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) tentang Hak Kesehatan. Intinya setiap orang, tanpa kecuali, berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
Nyeri dada fungsional atau organik ?
Proses hukum berpotensi besar menyebabkan seseorang mengalami stres. Gangguan emosi, bisa dipicu oleh stresor psikososial maupun stresor lainnya. Dampaknya berisiko memantik perubahan psikis, fisiologis, ataupun biokemis. Bahkan berisiko memunculkan suatu penyakit. Wujud homeostasis respons tubuh, bisa “diterjemahkan” dalam bentuk gejala psikis ataupun somatik. Secara umum, manifestasinya dikenal sebagai psikosomatik.
Keluhan yang ditampilkan, sangat bervariasi. Bisa timbul pada beberapa organ (multiorgan). Tetapi dapat juga hanya menonjol pada salah satu sistem organ tertentu saja. Keluhan yang menyangkut sistem kardiovaskuler, khususnya jantung, merupakan problem tersering. Bagi penegak hukum yang sedang menangani kasus tersebut, nyeri dada lazim diasosiasikan sebagai gangguan jantung. Meski demikian, bisa juga disebabkan etiologi lainnya. Karena itulah diperlukan kolaborasi dengan dokter yang berkompeten untuk memastikan diagnosisnya. Sebab stresor yang kuat, dapat memicu nyeri dada (angina pektoris). Kadang pula merupakan “aura” serangan jantung, sehingga memerlukan penanganan medis yang cepat dan tepat.
Korelasi antara gangguan psikis dengan penyakit jantung, telah lama menjadi perhatian para ahli. Polanya dapat digambarkan dalam tiga hal pokok. Pertama, gangguan jantung bisa hanya merupakan manifestasi yang sifatnya fungsional semata. Tidak akan berbahaya atau mengancam jiwa. Kedua, individu yang benar-benar sakit jantung, acap kali diikuti oleh perasaan tidak nyaman (disforia). Ketiga, gangguan psikis merupakan salah satu faktor risiko terjadinya penyakit jantung koroner (PJK).
Guna melakukan tatalaksana yang holistik, seorang dokter yang kompeten mesti dapat membedakan dua hal penting. Apakah keluhan nyeri dada tersebut bersifat fungsional saja atau organik. Bila organik, harus dapat dibuktikan secara ilmiah melalui suatu prosedur diagnostik yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya bila hasil tes diagnostik menunjukkan normal, bisa dikategorikan bersifat fungsional. Artinya merupakan representasi stres psikis atau psikosomatik belaka. Ringkasnya, gangguan jantung fungsional dapat menyerupai penyakit jantung organik. Sebaliknya, penyakit jantung organik, sering kali disertai gangguan psikis.
Stres psikis memantik peningkatan aktivitas sistem saraf otonom simpatis. Mekanismenya di luar kesadaran manusia. Efeknya memicu peningkatan denyut jantung, tekanan darah, atau bahkan gangguan irama jantung. Terjadi pula kontraksi arteri yang berlebihan pada limpa dan ginjal, dengan segala konsekuensinya. Pada gilirannya, berisiko memantik terjadinya trombosis (bekuan darah) pada pembuluh darah otak (stroke) dan jantung (infark jantung).
Peran legal dokter
Sebagai tindak lanjutnya, seorang dokter yang kompeten bisa memberikan rekomendasi dalam bentuk surat keterangan dokter (SKD). Pada dasarnya SKD, merupakan bukti tertulis yang menyatakan keadaan seseorang dalam keadaan sehat atau sakit. Tegasnya, SKD yang menyatakan seseorang sakit, memang perlu diberikan (sesuai indikasi medis) dan bukan karena diminta. Tetapi tidak jarang, SKD dapat “disalahgunakan” untuk berbagai kepentingan tertentu. Termasuk pula terhadap masalah hukum. SKD yang diterbitkan, harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dari sisi profesionalitas kedokteran. SKD juga harus memiliki tanggung jawab dari aspek hukum. Oleh karenanya, penerbitan suatu SKD mesti didasarkan pada suatu etika profesi, sumpah dokter, serta bersikap independen. Artinya, jangan demi “kepentingan tertentu” atau “di bawah tekanan”. Semuanya harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Secara eksplisit penerbitan SKD mengacu pada Kode Etik Kedokteran (KODEKI) Tahun 2012. Dalam Pasal 2 dan 3, menyatakan bahwa seorang dokter wajib selalu melakukan pengambilan keputusan profesional secara independen, dalam derajat yang tertinggi. Dalam melakukan pekerjaan profesional tersebut, tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi. Pada Pasal 7 menyatakan, seorang dokter wajib hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya.
Sebaliknya, dokter juga dapat dianggap secara moral melanggar kode etik profesi. Hal itu terbukti jika telah memberikan surat keterangan sakit kepada seseorang, tanpa melalui prosedur diagnostik yang telah ditentukan. Bila SKD dikeluarkan dengan sengaja tanpa melakukan pemeriksaan klinis secara langsung, dapat dituduh membuat surat keterangan palsu. Sudah barang tentu, perbuatan tersebut ada sanksi hukumnya (Pasal 267 KUHP).
—–o—–
*Penulis:
- Staf pengajar senior di Divisi Alergi-Imunologi Klinik, Departemen/KSM Ilmu Penyakit Dalam FK Unair/RSUD Dr. Soetomo – Surabaya
- Magister Ilmu Kesehatan Olahraga (IKESOR) Unair
- Penulis buku:
– Serial Kajian COVID-19 (tiga seri)
– Serba-serbi Obrolan Medis
– Catatan Harian Seorang Dokter

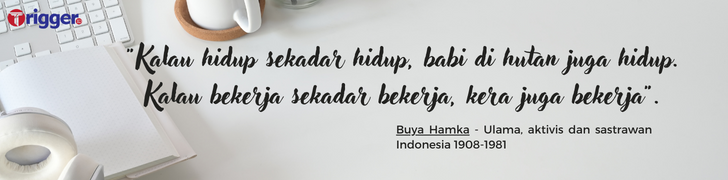

Tinggalkan Balasan